K.H. Muhammad Dahlan
MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia)
Golongan nasionalis Islam adalah golongan yang sangat anti Barat, hal
itu sesuai dengan apa yang diinginkan Jepang. Jepang berpikir bahwa golongan
ini adalah golongan yang mudah dirangkul. Untuk itu, sampai dengan bulan
Oktober 1943, Jepang masih mentoleransi berdirinya MIAI. Pada pertemuan
antara pemuka agama dan para gunseikan yang diwakili oleh Mayor Jenderal
Ohazaki di Jakarta, diadakanlah acara tukar pikiran. Hasil acara ini dinyatakan
bahwa MIAI adalah organisasi resmi umat Islam. Meskipun telah diterima
sebagai organisasi yang resmi, tetapi MIAI harus tetap mengubah asas dan
tujuannya. Begitu pula kegiatannya pun dibatasi. Setelah pertemuan ini, MIAI
hanya diberi tugas untuk menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam
dan pembentukan Baitul Mal (Badan Amal). Ketika MIAI menjelma menjadi
sebuah organisasi yang besar maka para tokohnya mulai mendapat pengawasan,
begitu pula tokoh MIAI yang ada di desa-desa.
Lama kelamaan Jepang berpikir bahwa MIAI tidak menguntungkan Jepang,
sehingga pada bulan Oktober 1943 MIAI dibubarkan, lalu diganti dengan
Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan dipimpin oleh K.H Hasyim
Asy’ari, K.H Mas Mansyur, K.H Farid Ma’ruf, K.H. Hasyim, Karto Sudarmo,
K.H Nachrowi, dan Zainul Arifin sejak November 1943.
Jika dilihat lebih saksama, secara politis pendudukan Jepang telah mengubah
beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.
a. Berubahnya pola perjuangan para pemimpin Indonesia, yaitu dari perjuangan
radikal menuju perjuangan kooperatif (kerja sama). Hal ini dimanfaatkan
oleh para pemimpin Indonesia untuk membina mental rakyat. Misalnya
melalui keterlibatan rakyat dalam Putera dan Jawa Hokokai.
b. Berubahnya struktur birokrasi, yaitu dengan membagi wilayah ke dalam
wilayah pemerintah militer pendudukan. Misalnya, diperkenalkannya sistem
tonarigumi (rukun tetangga) di desa-desa. Lalu beberapa gabungan
tonarigumi ini dikelompokkan ke dalam ku (desa atau bagian kota).
Akibat ini semua, desa menjadi lebih terbuka dan banyak juga dari orang
Indonesia yang menduduki jabatan birokrasi tinggi di pemerintahan, suatu
hal yang tidak terjadi pada masa pemerintahan Belanda.
Golongan nasionalis Islam adalah golongan yang sangat anti Barat, hal
itu sesuai dengan apa yang diinginkan Jepang. Jepang berpikir bahwa golongan
ini adalah golongan yang mudah dirangkul. Untuk itu, sampai dengan bulan
Oktober 1943, Jepang masih mentoleransi berdirinya MIAI. Pada pertemuan
antara pemuka agama dan para gunseikan yang diwakili oleh Mayor Jenderal
Ohazaki di Jakarta, diadakanlah acara tukar pikiran. Hasil acara ini dinyatakan
bahwa MIAI adalah organisasi resmi umat Islam. Meskipun telah diterima
sebagai organisasi yang resmi, tetapi MIAI harus tetap mengubah asas dan
tujuannya. Begitu pula kegiatannya pun dibatasi. Setelah pertemuan ini, MIAI
hanya diberi tugas untuk menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam
dan pembentukan Baitul Mal (Badan Amal). Ketika MIAI menjelma menjadi
sebuah organisasi yang besar maka para tokohnya mulai mendapat pengawasan,
begitu pula tokoh MIAI yang ada di desa-desa.
Lama kelamaan Jepang berpikir bahwa MIAI tidak menguntungkan Jepang,
sehingga pada bulan Oktober 1943 MIAI dibubarkan, lalu diganti dengan
Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan dipimpin oleh K.H Hasyim
Asy’ari, K.H Mas Mansyur, K.H Farid Ma’ruf, K.H. Hasyim, Karto Sudarmo,
K.H Nachrowi, dan Zainul Arifin sejak November 1943.
Jika dilihat lebih saksama, secara politis pendudukan Jepang telah mengubah
beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.
a. Berubahnya pola perjuangan para pemimpin Indonesia, yaitu dari perjuangan
radikal menuju perjuangan kooperatif (kerja sama). Hal ini dimanfaatkan
oleh para pemimpin Indonesia untuk membina mental rakyat. Misalnya
melalui keterlibatan rakyat dalam Putera dan Jawa Hokokai.
b. Berubahnya struktur birokrasi, yaitu dengan membagi wilayah ke dalam
wilayah pemerintah militer pendudukan. Misalnya, diperkenalkannya sistem
tonarigumi (rukun tetangga) di desa-desa. Lalu beberapa gabungan
tonarigumi ini dikelompokkan ke dalam ku (desa atau bagian kota).
Akibat ini semua, desa menjadi lebih terbuka dan banyak juga dari orang
Indonesia yang menduduki jabatan birokrasi tinggi di pemerintahan, suatu
hal yang tidak terjadi pada masa pemerintahan Belanda.














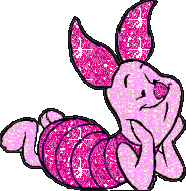
0 komentar:
Posting Komentar